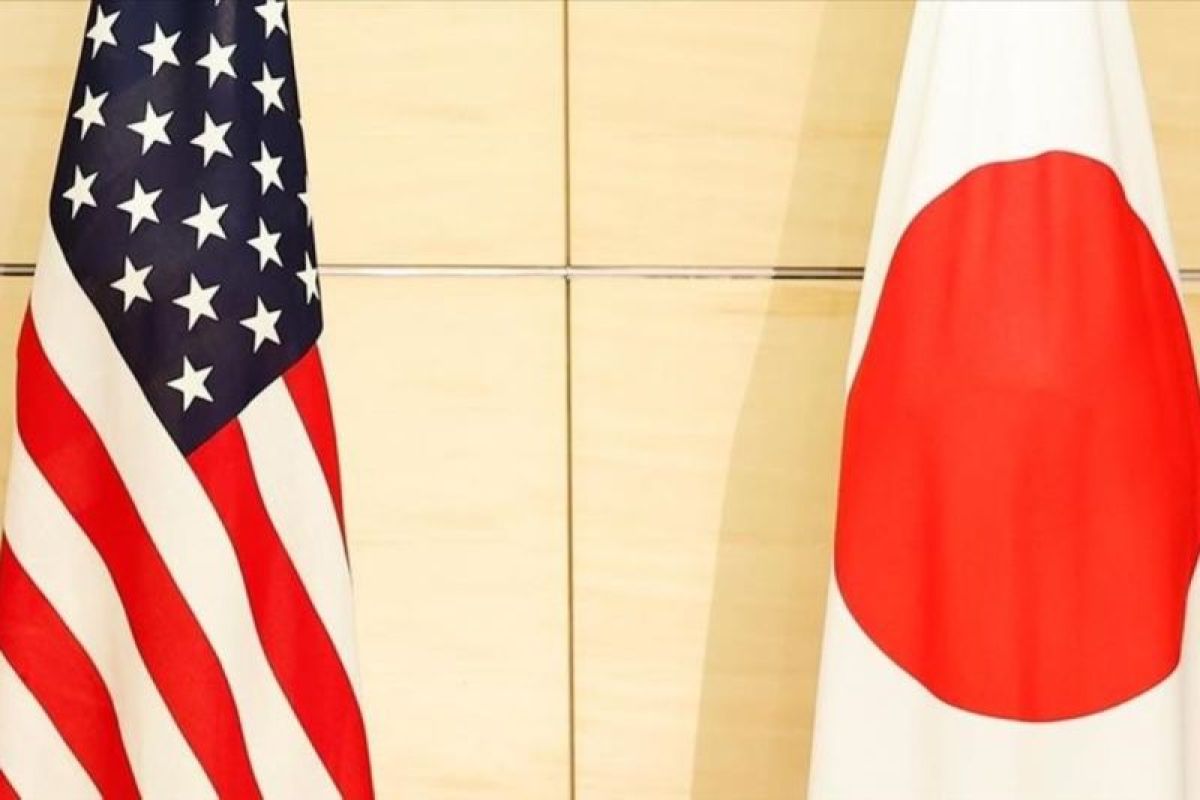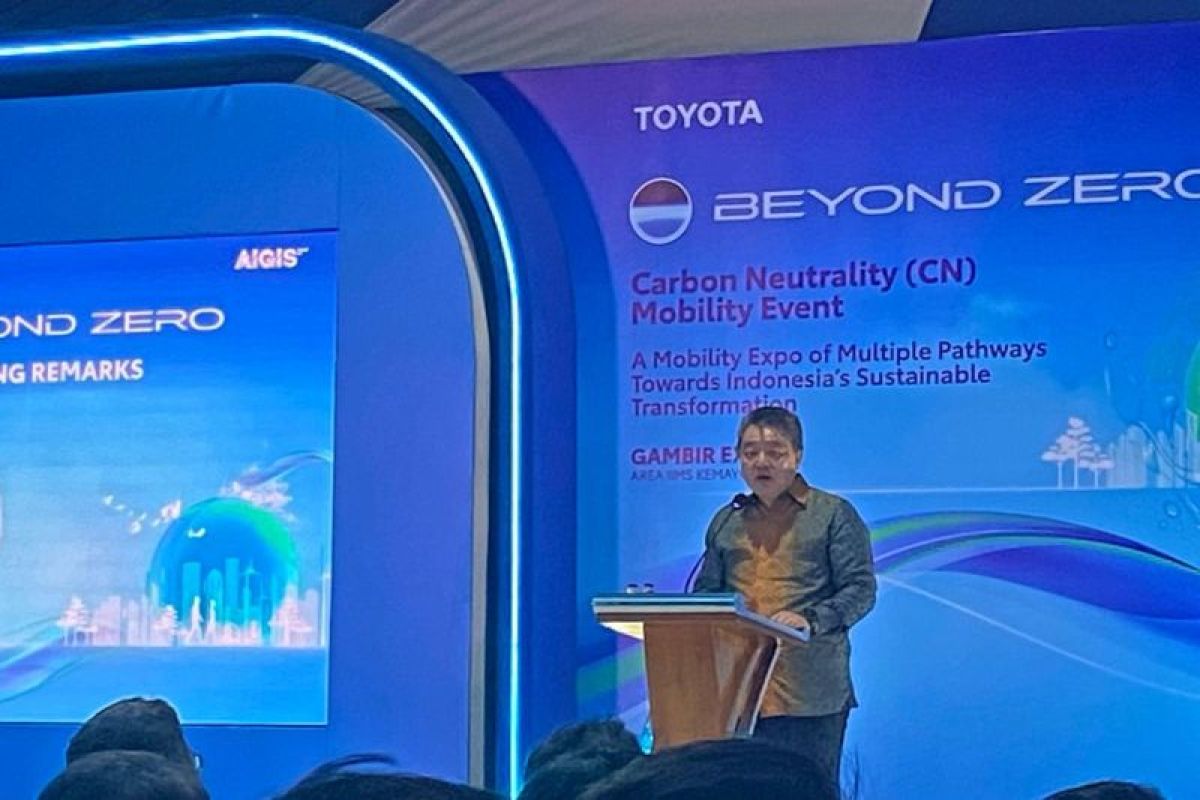Bandung (ANTARA) - Di tengah derasnya pemberitaan tentang dunia yang terus saling berteriak terpicu polah random Trump, kabar wafatnya Paus Fransiskus datang seperti interupsi yang tidak diundang tapi sarat makna.
Seperti dilaporkan Vatican News, Sri Paus wafat dalam usia 88 tahun di kediamannya pukul 7:35 Senin pagi waktu Vatikan, setelah mengalami sakit berkepanjangan.
Pemimpin Gereja Katolik itu tidak pergi dengan dramatis, tidak juga dengan senyap. Dia pergi seperti cara dia memimpin: perlahan, konsisten, dan penuh paradoks.
Pada awal Februari 2025, Sri Paus dirawat di Rumah Sakit Gemelli setelah menderita bronkitis selama beberapa hari. Kondisinya semakin memburuk, dan pada 18 Februari, dia didiagnosis menderita pneumonia bilateral yang akhirnya pulang ke kediamannya setelah dirawat selama 38 hari.
Wafatnya Fransiskus membuat dunia kehilangan seorang pemimpin moral yang tidak berbicara dari menara gading, tapi dari jalanan, rumah tahanan, perahu pengungsi, dan ladang terbakar. Dia wafat dengan meninggalkan warisan spiritual dan etika yang memberi gizi pada dunia yang semakin absurd.
Sebagian orang menyebut dia sebagai “Paus dari rakyat.” Sebagian lagi menyebut “gembala yang beraroma domba." Barangkali yang paling pas adalah deskripsi yang pernah ia ucapkan tentang dirinya sendiri, “Saya seorang pendosa yang dikasihi oleh Allah.”
Pernyataan diri itu sama sekali bukan retorika. Itu adalah fondasi seluruh kepemimpinannya, bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh cinta kasih.
Sebagai pemimpin Gereja Katolik Roma, pemilik nama lahir Jorge Mario Bergoglio itu lebih menyerupai seorang peziarah spiritual ketimbang kepala negara mini yang bersemayam di Vatikan. Sejak awal, pria asal Buenos Aires itu tampak tak tertarik untuk menjadi sosok paus seperti yang orang-orang bayangkan. Ia menolak tinggal di istana apostolik (Palazzo Apostolico) dan lebih memilih rumah tamu Vatikan. Ia menyukai sepatu biasa, menyapa orang biasa, dan bicara dengan bahasa biasa.
Di zaman ketika banyak pemimpin agama berlomba menjadi selebriti spiritual atau aktivis media sosial, Fransiskus tetap Bergoglio yang bersahaja. Ia tidak mudah dikotak-kotakkan, tidak gampang dilabeli.
Di Indonesia, kabar wafatnya Paus Fransiskus datang seperti kabut pagi yang menyusup pelan, tapi menyisakan kesyahduan yang dalam. Di Kapel Katedral Jakarta, lilin dinyalakan. Di NTT, lonceng gereja dibunyikan. Di banyak tempat, umat Katolik dan lintas agama menggelar doa bersama.
Indonesia jelas bukan negara Katolik, tapi Indonesia tahu betul artinya hidup dalam kebinekaan yang rapuh. Kita hidup dalam realitas saat ego sektoral seringkali lebih bising daripada kemanusiaan; Ketika agama masih terlalu sering dijadikan alat politik, bukan ruang perenungan.
Dalam konteks inilah warisan Fransiskus terasa relevan. Dia tidak menawarkan doktrin, Dia menawarkan kemungkinan. Dalam setiap pernyataannya tentang kemiskinan, migrasi, krisis iklim, atau keberagaman gender, Paus Fransiskus tampak lebih seperti seorang penyair sosial ketimbang teolog. Dia berbicara tentang manusia, bukan hanya tentang iman. Dia mengingatkan bahwa spiritualitas tidak selalu harus dipertontonkan, dan bahwa welas asih tidak mengenal mazhab.
Bangsa Indonesia dengan keberagamannya yang elok sekaligus rapuh, sesungguhnya memiliki banyak kesamaan visi dengan Fransiskus.; Sri Paus mewartakan perdamaian di tengah kebinekaan, kita mengangkat semboyan “Bhinneka Tunggal Ika"; Sri Paus menyebut agama sebagai jalan dialog, kita punya forum antarumat; Sri Paus bicara tentang ekonomi yang memihak wong cilik, kita pun terus berjibaku dengan ketimpangan.
Dalam banyak hal, Paus Fransiskus juga pengingat bahwa agama tidak harus menjadi suara konservatisme yang membatu, melainkan bisa menjadi suara kebenaran yang terus bergerak, terus bertanya, dan tidak takut berubah. Sebuah pelajaran penting untuk semua agama yang kerap gamang di antara tradisi dan kebutuhan untuk beradaptasi.
Satu lagi warisan terbesar Paus Fransiskus adalah keberaniannya untuk berkata yang tak ingin didengar oleh logika kekuasaan. Dia menyebut kapitalisme yang tak terkendali sebagai “eksklusi sosial terselubung.” Dia menyebut dunia yang menutup pintu bagi pengungsi sebagai “kehilangan kemanusiaan.” Dia menyebut pelecehan seksual dalam gereja sebagai “luka yang dalam dan memalukan.” Bahkan, tentang Gaza dia menghentak dengan menyatakan “terjadinya kekerasan tak berujung.”
Bagi sebagian orang, ucapan Fransiskus itu cukup mengguncang, atau biasa-biasa saja. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin justru membuka harapan. Seperti rakyat Palestina yang melihat setitik asa ketika Sang Pemimpin Umat Katolik itu menyebut invasi Israel di Gaza sebagai “kekejaman luar biasa.” Rakyat Palestina pun menyatakan duka mendalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus yang mereka sebut sebagai seorang teman sejati.
“Hari ini, Palestina kehilangan seorang teman setia bagi rakyat Palestina dan hak-hak mereka,” ucap Presiden Palestina Mahmoud Abbas, melalui pernyataan tertulis yang dipantau di laman X Perwakilan Palestina untuk PBB @Palestine_UN, Senin.
Dengan kepergian Paus Fransiskus, dunia menghadapi ruang kosong yang tidak bisa langsung diisi oleh Paus berikutnya, siapa pun dia, karena Fransiskus bukan sekadar pejabat Paus. Dia adalah semacam simbol dari paradoks yang konstrukif: bahwa kekuatan bisa lembut, bahwa otoritas bisa membumi, bahwa suara spiritual tidak harus keras untuk bisa didengar.
Meski jauh, kita di Indonesia seharusnya bisa menangkap paradoks itu dengan jernih. Dalam kegaduhan sehari-hari kita, mulai dari polemik kebebasan beragama hingga deret panjang konflik industrial dan sosial, warisan Fransiskus menjadi semacam referensi etika yang tidak memaksa, tapi mengundang.
Dia tidak memberi resep, hanya menyodorkan cermin. Seperti cermin yang baik, dia tidak menjawab, hanya memantulkan.
Copyright © ANTARA 2025

 5 days ago
22
5 days ago
22