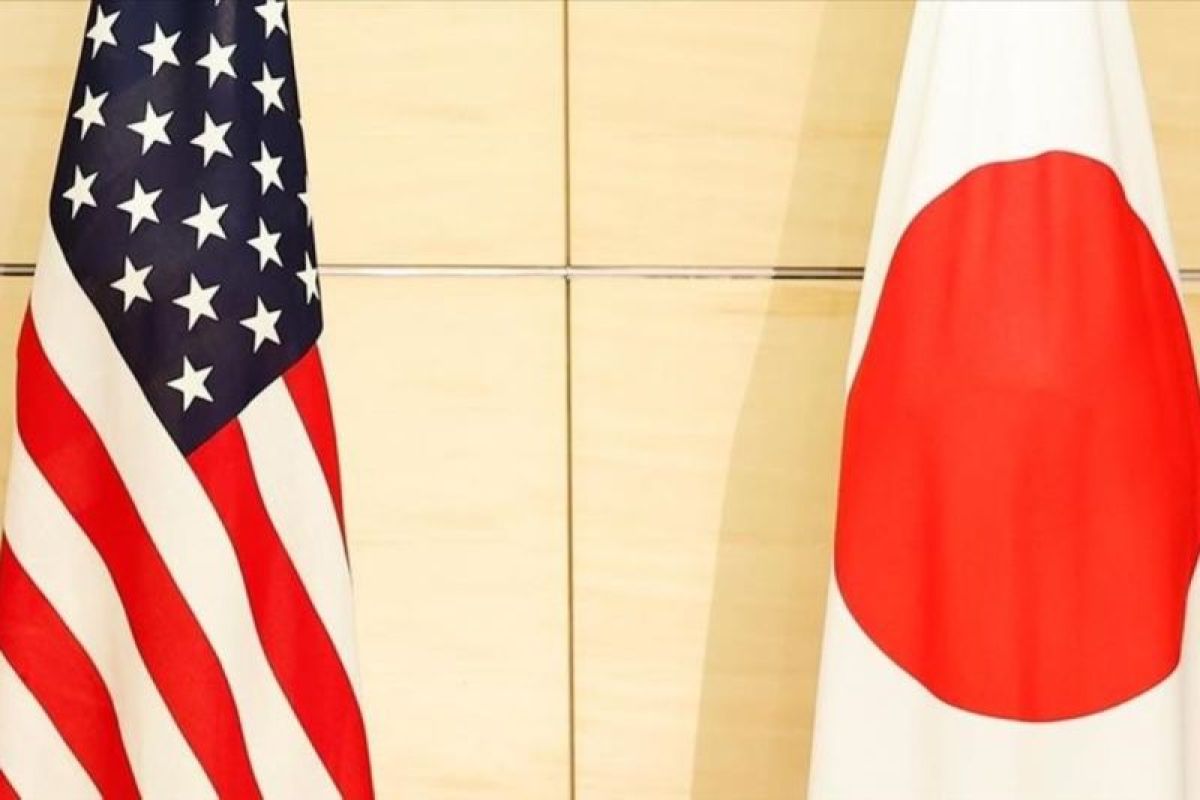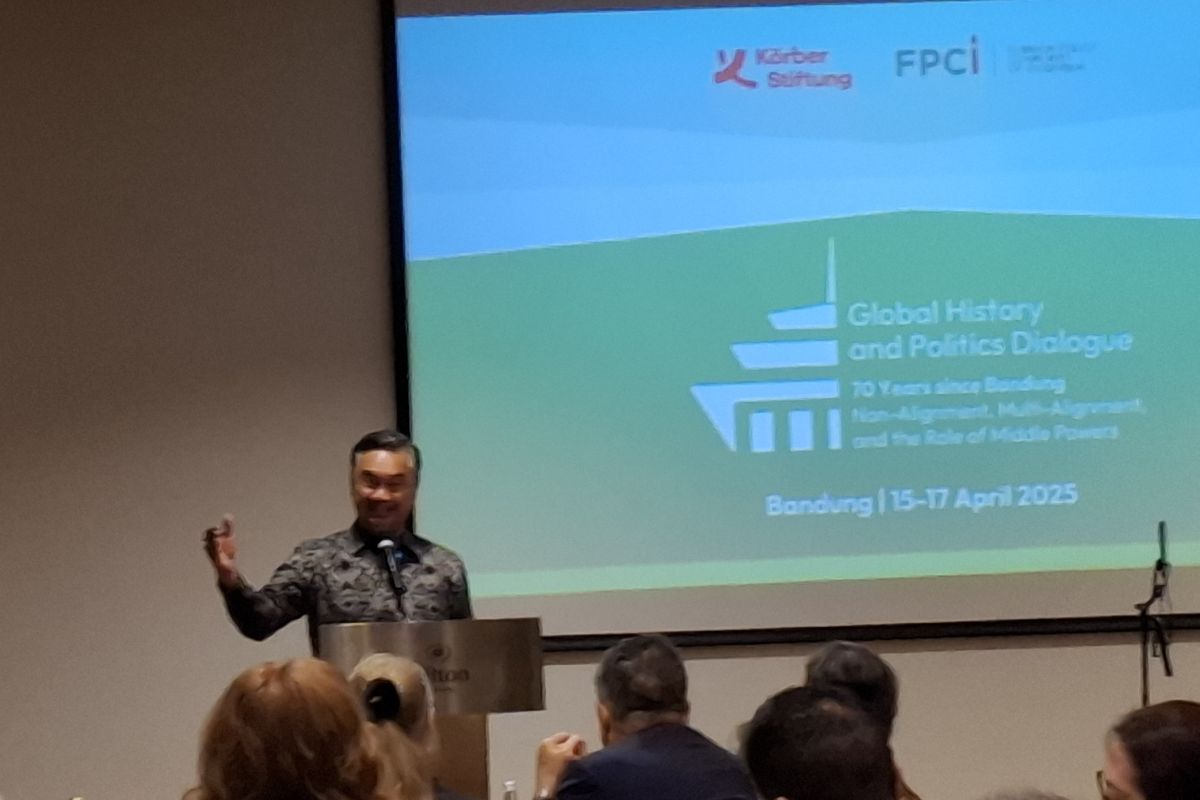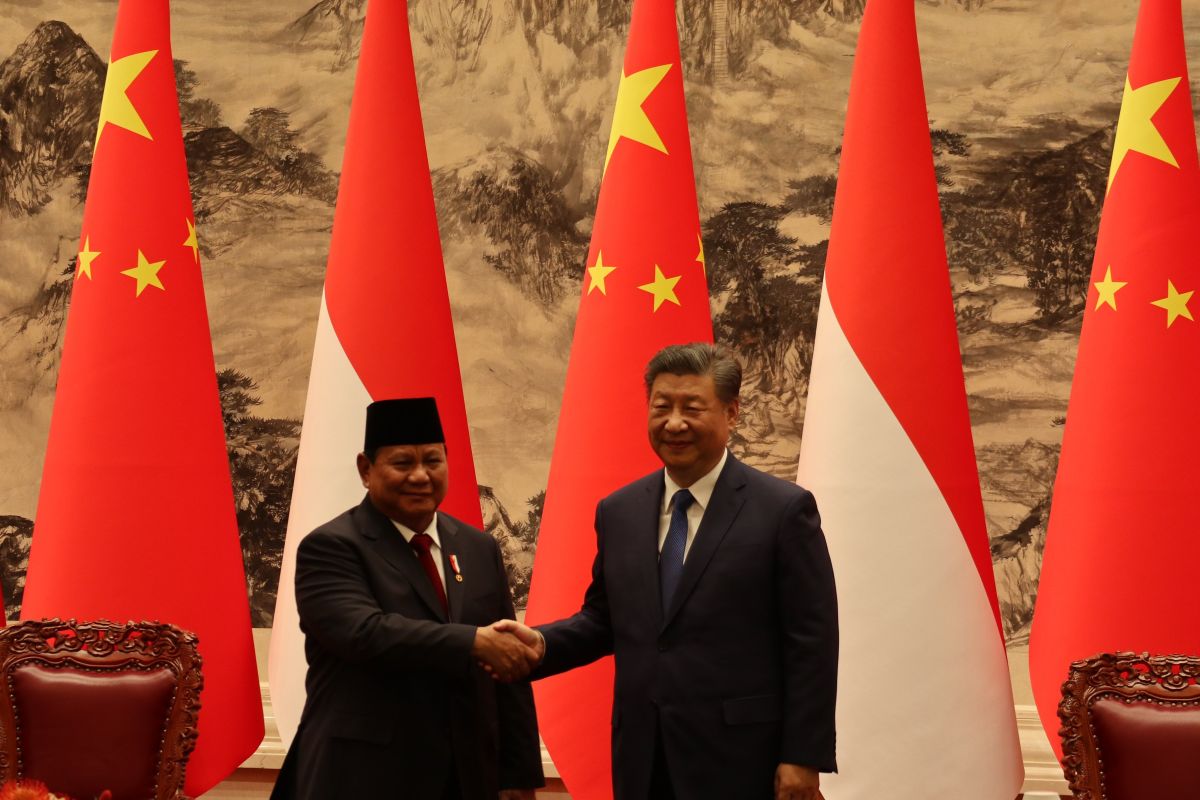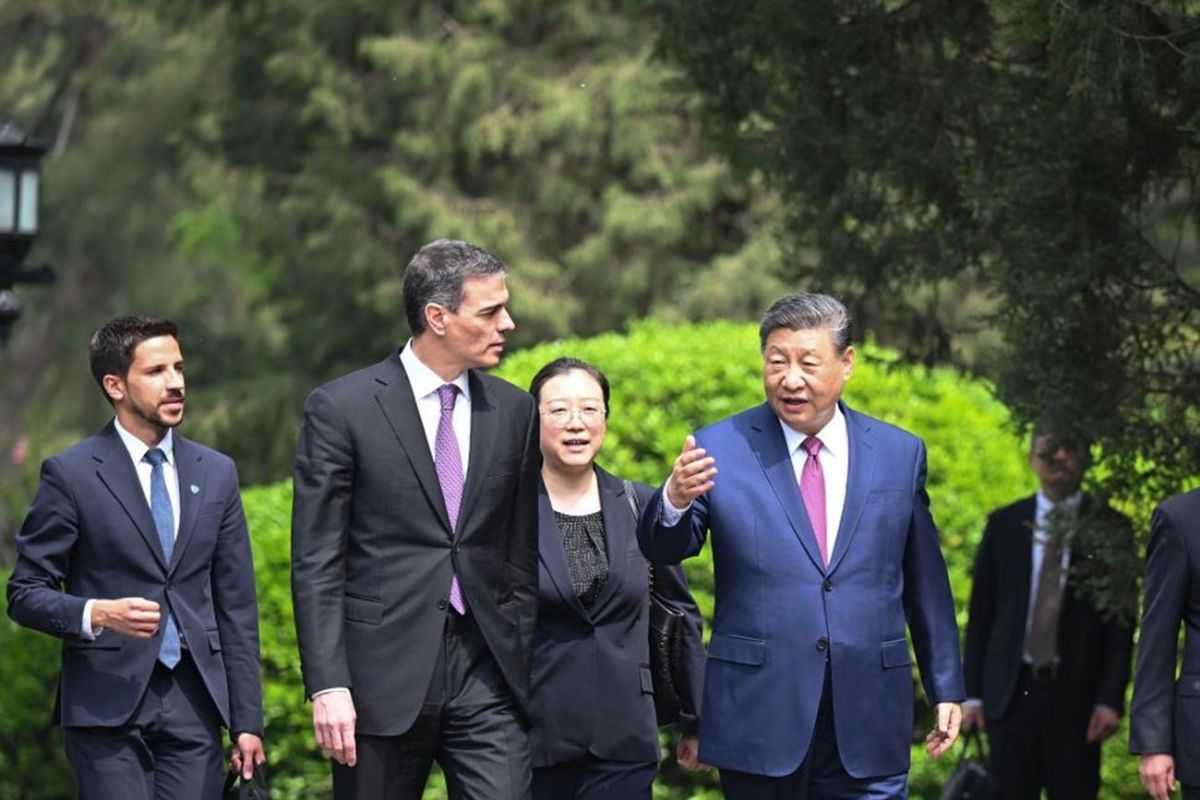Jakarta (ANTARA) - Sejak pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat pada 2016, Donald Trump menempatkan dirinya sebagai orang yang sulit ditebak.
Dia bahkan pernah berkata bahwa AS harus menjadi negara yang sulit diprediksi karena dengan cara itu lawan kesulitan menebak AS sehingga tak memiliki pilihan selain menuruti tuntutan AS.
Trump berusaha memperlihatkan diri sebagai orang yang nekad, bahkan gila, sehingga pihak lain takut membayangkan konsekuensi kegilaannya untuk kemudian menuruti gertakan-gertakannya.
Dalam politik internasional, keinginan untuk terlihat sulit diprediksi itu disebut dengan "Madman Theory" atau "Teori Orang Gila."
Ini adalah teori tentang pemimpin yang tindakan-tindakan dan pandangan-pandangannya tak segan berkonflik, dengan tujuan utama membuat lawan ketakutan dan akhirnya memberikan konsesi.
Trump sendiri kerap sesumbar bahwa lawan-lawannya takut kepadanya karena tak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan kepada mereka.
Istilah "Madman Theory" pertama kali keluar dari mulut Richard Nixon, presiden AS pada 1969-1974, semasa Perang Vietnam.
Kala itu Nixon berusaha memaksa Vietnam Utara atau Vietcong agar mengakhiri perang.
Vietcong memang sulit sekali diajak berunding, sampai Nixon memberi pesan kepada para pemimpin mereka bahwa dia bisa nekad melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh orang gila.
"Saya menyebutnya 'Teori Orang Gila', Bob. Saya ingin Vietnam Utara percaya bahwa saya sudah sampai pada titik bahwa saya akan melakukan apa saja untuk menghentikan perang ini," kata Nixon kepada kepada kepala staf kepresidenannya, Bob Haldeman.
Ternyata, Vietnam Utara dan juga Uni Soviet yang menjadi sekutu utama Vietcong, termakan oleh gambaran bahwa Nixon "orang gila" yang bisa berbuat nekad, termasuk melancarkan serangan nuklir seperti saat menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada 1945.
Vietcong akhirnya mau berunding pada 1972, walau Perang Vietnam baru berakhir tiga tahun kemudian akibat posisi AS yang terus didesak Vietcong.
Sebenarnya banyak pemimpin dunia yang berpura-pura gila, jauh sebelum Nixon mencetuskan "Madman Theory".
Itu termasuk Adolf Hitler pada Perang Dunia II dan pemimpin Uni Soviet Nikita Kruschchev yang menggertak AS dengan menggelarkan senjata nuklir di Kuba pada Oktober 1962.
Baca juga: Negosiasi tarif RI-AS berpotensi ciptakan neraca dagang yang seimbang
Kadang perlu berpura-pura gila
Pemikir politik termasyhur, Niccolo Machiavelli, dalam "Discourses on Livy", menyatakan "berpura-pura gila itu kadang hal yang bijaksana sekali."
Bijaksana dalam kaitan dengan bagaimana kekuasaan berhubungan dengan entitas kekuasaan lainnya.
Itulah yang tampaknya sedang dipraktikkan Donald Trump, tak saja di arena politik dan militer, tapi juga ekonomi, dari Perang Rusia-Ukraina dan Perang Gaza, sampai perang dagang.
Trump terlihat berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin yang tidak rasional dan sulit diprediksi yang bisa nekad melakukan apa pun sampai mendapatkan konsesi-konsesi yang dia inginkan dari pihak lain.
Cara sepihak Trump dalam memberlakukan tarif impor kepada puluhan negara termasuk Indonesia awal April ini, bisa dipahami dari "Teori Orang Gila" ini.
Teori sama bisa dipakai untuk menjelaskan provokasi-provokasi Trump dalam negosiasi dagang, setelah memberi waktu 90 hari kepada puluhan negara guna merundingkan lagi kontrak dagang dengan AS, usai menurunkan tarifnya menjadi flat 10 persen.
Langkah lebih gilanya kepada China, yang dijatuhi tarif impor sampai 145 persen, juga bisa dipahami dari perspektif "Madman Theory".
Trump juga mengaplikasikannya dalam kebijakan luar negerinya, termasuk dalam konteks Perang Gaza, Perang Ukraina dan ofensif diplomatiknya terhadap Iran dalam kaitan penguasaan nuklir oleh negara di Timur Tengah itu.
Di satu sisi, dengan cara itu Trump efektif menekan Israel agar menyepakati gencatan senjata di Gaza, membuat Presiden Rusia Vladimir Putin memikirkan lagi negosiasi guna mengakhiri perang di Ukraina, dan memaksa Iran berunding langsung dengan AS.
Tapi di sisi lain, karena gebrakan-gebrakan Trump itu kerap merupakan manuver jangka pendek, maka dia acap tak menawarkan peta jalan menyeluruh nan langgeng dalam sebuah konflik, entah konflik politik atau ekonomi.
Yang dominan dilihat orang-orang adalah semua itu ternyata melulu soal kepentingan sesaat AS.
Lebih buruk lagi, orang menjadi melihat bahwa Trump sebenarnya tidak gila. Sebaliknya, dia adalah makhluk kalkulatif yang sama rasionalnya dengan pemimpin pada umumnya, ketika sudah menyangkut konsekuensi dari berkebijakan.
Contoh, saat dia menjatuhkan tarif 145 persen kepada China, ternyata kebijakan ini membuat sejumlah produk AS menjadi sangat mahal bagi rakyat AS sendiri.
Taruhlah harga iPhone, yang awalnya 1.000 dolar AS, melambung menjadi 2.450 dolar AS gara-gara tarif. Ini sangat memberatkan konsumen AS, apalagi menurut Christian Science Monitor, 3 dari setiap 4 produk iPhone yang dijual di AS, dibuat di China.
Dihadapkan kepada kenyataan pahit ini, Trump lalu membuat kekecualian untuk sejumlah produk, termasuk iPhone, bahwa tarif 145 persen tak berlaku untuk produk-produk kekecualian ini.
Padahal, Trump sebelumnya kerap sesumbar tak akan membuat pengecualian dalam konteks perang tarif.
Baca juga: Trump klaim negara-negara lain minta penurunan tarif
Baca juga: Donald Trump pertimbangkan untuk larang warga AS pakai AI DeepSeek
Lebih sering gagal ketimbang berhasil
Karena menyadari akibat dari kebijakan-kebijakannya, Trump menjadi terlihat berubah-ubah.
Dia menunda penerapan tarif dari awalnya 9 April menjadi 90 hari kemudian, karena mendapati kenyataan pahit perang tarif malah membuat surat utang pemerintah AS jatuh, yang menjadi petunjuk bahwa pasar mulai tak mempercayai instrumen investasi paling aman di dunia itu. Dan ini buruk akibatnya bagi keseluruhan sistem perekonomian AS.
Di medan politik, Trump juga ternyata rasional dalam mengkalkulasi akibat dari setiap dinamika yang terjadi di Gaza dan Ukraina, dalam kaitan posisi politik AS di dunia.
Artinya, Trump menyadari dan menghitung konsekuensi dari kebijakannya, yang dalam kata lain dia sama sekali bukan orang gila.
Sayangnya, karena Trump adalah presiden sebuah negara adidaya yang postur ekonomi, politik dan militernya sangat meraksasa sampai menentukan gerak dunia, maka tetap saja bagian besar dunia mengkhawatirkan Trump akan berbuat nekad.
Hanya sedikit negara yang selain menyadari Trump tidak segila manuver-manuver politiknya, tapi juga sanggup menghadapi "kepura-pura gilaan" yang ditunjukkan Trump.
Negara seperti ini memiliki kapabilitas power yang setara dengan AS, sehingga sanggup melakukan hal-hal yang sama gilanya dengan Trump.
Kabar baiknya, negara ini masih setia dengan globalisasi, perdagangan bebas, dan multilateralisme.
Sayangnya, negara itu cuma satu, dan itu adalah China.
China pula yang terus melawan Trump, ketika bagian terbesar dunia terpojok oleh Trump, sehingga kendati mengeluh karena ditekan AS, tak bisa berbuat apa-apa selain menerima tekanan itu, termasuk tuntutan mengubah pasal-pasal dalam kontrak dagang sehingga menjadi lebih menguntungkan industri AS.
Kabar baik lainnya, menurut sejumlah pakar Hubungan Internasional di Barat, "Madman Theory" lebih sering gagal, ketimbang berhasil.
Ini karena pemimpin yang menerapkan teori ini kerap kesulitan memberikan janji yang kredibel. Dan itu pula yang tengah terjadi pada Trump, yang memang berubah-ubah sehingga janji-janjinya tidak bisa dianggap kredibel.
Sejumlah negara dan kawasan yang tak sekuat China sebenarnya menyadari kelemahan itu.
Negara-negara seperti ini tak terang-terangan melawan seperti China, melainkan dengan merekatkan kerja sama antar mereka, sambil menuruti sebagian tuntutan Trump, kendati terpaksa.
Mereka mungkin berpikir tokh ini hanya sementara, sampai Trump tak lagi berkuasa di AS, atau sampai dia digoyang di tengah jalan oleh opini publik di dalam negerinya.
Baca juga: Semangat Bandung 1955 dalam tiupan Trumpisme
Baca juga: Trump sebut China berusaha berunding setelah tarif AS diberlakukan
Baca juga: Strategi pertahanan "opportunity in tightness" di tengah Trump tariff
Copyright © ANTARA 2025

 6 hours ago
2
6 hours ago
2