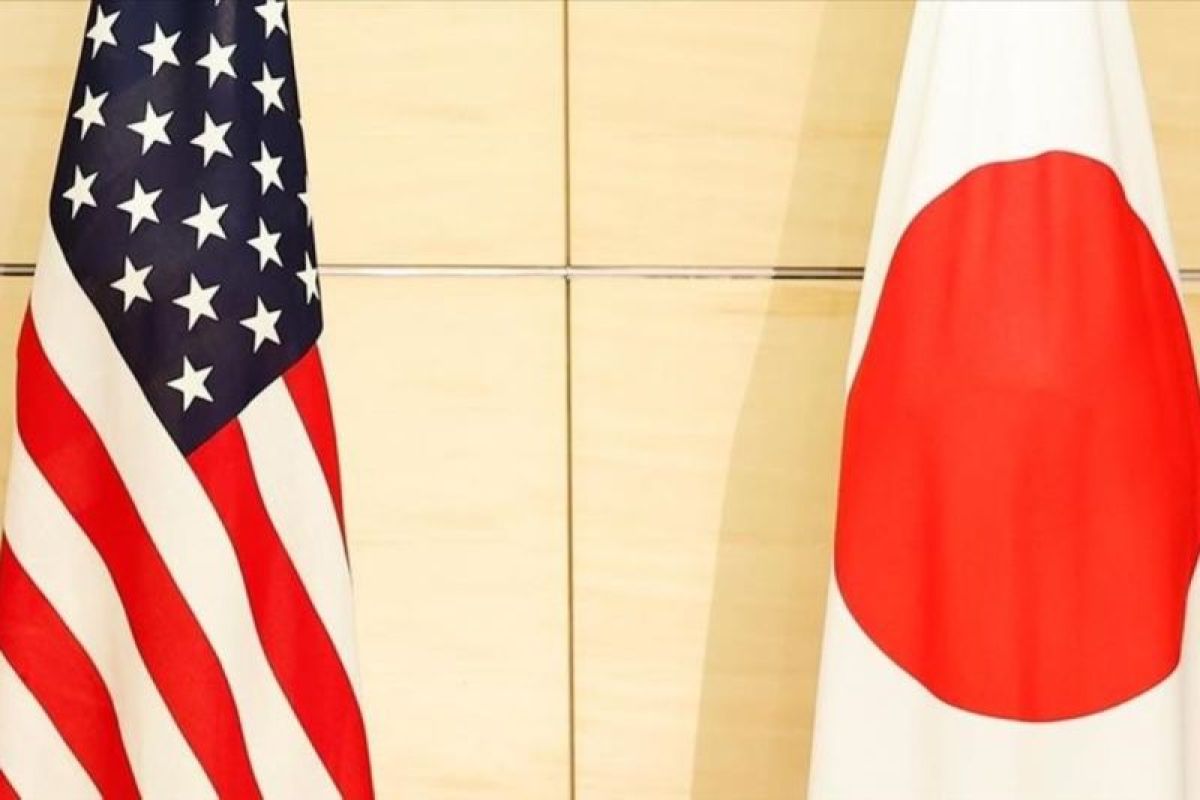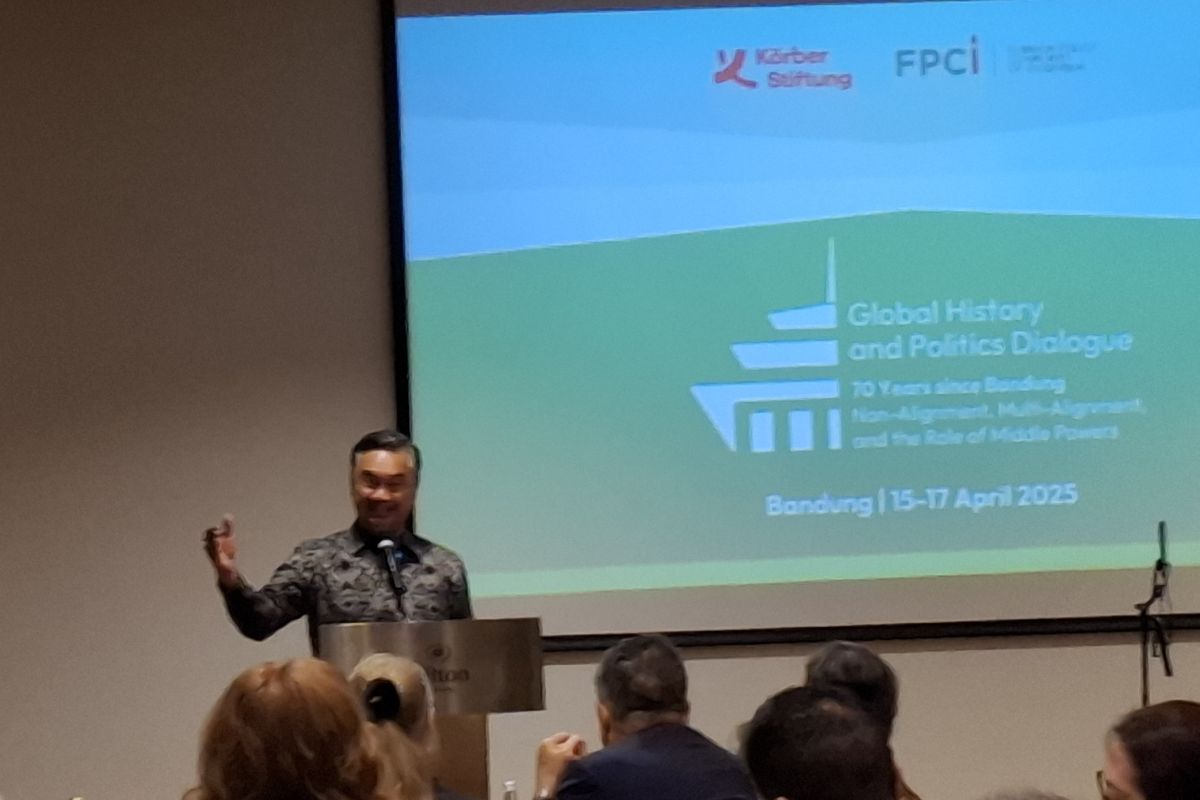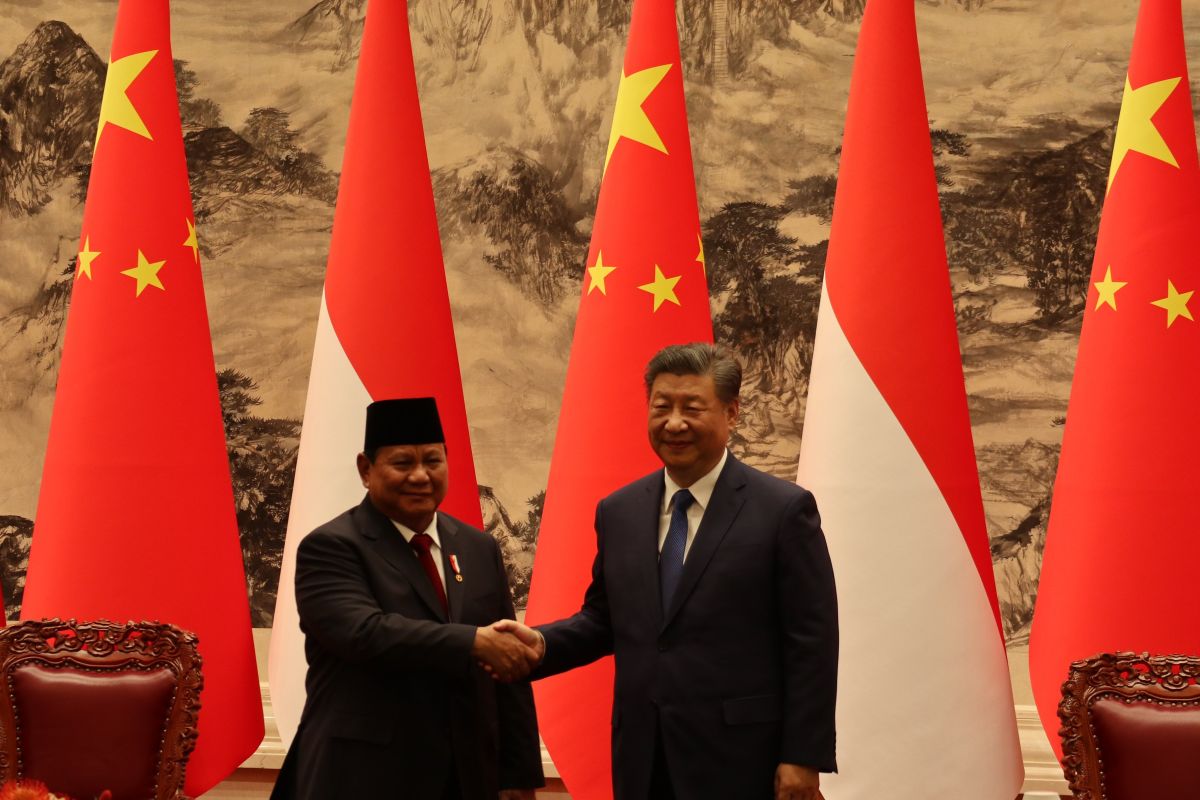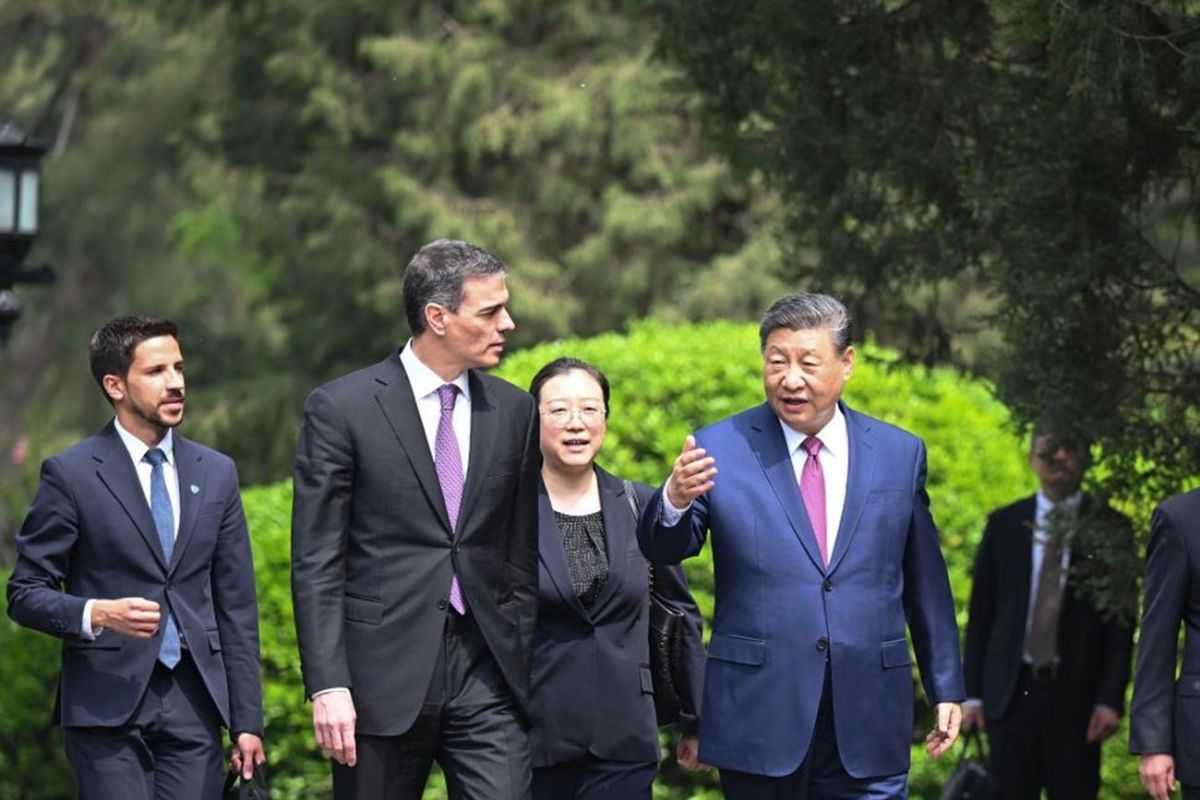Jakarta (ANTARA) - Seorang Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa dirinya secara tulus dan memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan sebuah kelompok masyarakat di suatu daerah.
Namun, Presiden AS itu menyatakan bahwa syaratnya bahwa kelompok masyarakat tersebut harus meninggalkan rumah yang telah ditempati mereka sejak bergenerasi-generasi karena kehidupan mereka dinilai tidak sesuai dengan kemajuan di wilayah negara tersebut.
Pesan tersebut bukanlah dikemukakan oleh Donald Trump kepada warga Gaza di tahun 2025 ini, tetapi itu adalah laporan tahunan kepada Kongres yang disampaikan oleh Presiden AS Andrew Jackson pada 1830, setelah dia menandatangani Indian Removal Act atau UU Pemindahan Suku Indian.
UU Pemindahan Suku Indian adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS dan ditandatangani oleh Presiden Andrew Jackson pada tanggal 28 Mei 1830. Tujuan utama langkah penggusuran itu adalah untuk mengizinkan relokasi suku asli Amerika yang tinggal di AS bagian tenggara ke wilayah sebelah barat Sungai Mississippi, di tempat yang sekarang disebut sebagai Oklahoma.
Penyebabnya, AS yang pada awal abad ke-19 mengembangkan dengan pesat daerahnya sehingga semakin banyak pemukim yang berdatangan ke wilayah yang telah dihuni secara berabad-abad oleh suku asli di sana.
Melihat adanya lahan yang subur di wilayah suku Indian, para pemukim kulit putih ingin menguasainya guna memperluas area perkebunan kapas dengan tenaga kerja budak yang dimiliki para pemukim itu. UU yang dasarnya merupakan upaya pemindahan paksa suku Indian itu disahkan dengan dukungan sebagian besar anggota Kongres, khususnya legislator yang berasal dari negara bagian AS selatan yang mendukung perbudakan.
Produk legislasi Kongres AS itu membuat pemerintah Paman Sam menyediakan dana untuk penggusuran suku Indian, serta menggunakan dukungan sumber daya militer. Akibat dari pemindahan paksa puluhan ribu penduduk asli AS itu, banyak dari warga suku Indian yang tewas karena kondisi buruk dan penyakit.
Presiden Jackson menggambarkan pemindahan tersebut sebagai langkah penting demi "kesejahteraan" penduduk asli Amerika, dengan menganggap cara hidup tradisional mereka tidak sesuai dengan kemajuan Amerika Serikat.
Senada, Wakil Presiden AS John Calhoun meyakini bahwa penduduk asli Amerika "tidak beradab" dan tidak mampu hidup berdampingan dengan pemukim yang datang dari Eropa. Dia membenarkan pemindahan tersebut sebagai cara untuk menjaga penduduk asli Amerika tetap berada di wilayah yang dianggap "kurang berguna" untuk pertanian dan ekspansi oleh populasi pemukim.
Menteri Perang Lewis Cass pada saat itu juga menegaskan bahwa pengusiran orang-orang suku Indian adalah tindakan yang sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keselamatan suku-suku Indian itu sendiri. Berbagai kutipan dari politisi AS abad ke-19 itu merupakan bagian dari retorika yang digunakan oleh para pendukung langkah penghapusan suku Indian, yang menggambarkan suku asli Amerika sebagai hambatan bagi kemajuan dan stabilitas politik untuk membenarkan relokasi paksa ke tempat reservasi.
Baca juga: Meski bantuan terancam dipangkas, Raja Yordania tolak rencana Trump
Baca juga: Pakar: Rencana Trump ambil alih Gaza melanggar hukum internasional
Jejak Air Mata
UU tersebut mengakibatkan peristiwa pemindahan paksa yang dikenal di catatan sejarah AS sebagai "Trail of Tears" (Jejak Air Mata). Dari tahun 1838 hingga 1839, sekitar 16.000 orang suku Indian Cherokee (salah satu suku dari banyak kelompok yang digusur otoritas AS) terpaksa meninggalkan rumah mereka di Georgia dan negara bagian AS sekitarnya.
Mereka tidak punya banyak pilihan selain memulai perjalanan ke lokasi baru yang jaraknya lebih dari 1.200 kilometer. Para warga yang juga terdiri dari banyak keluarga itu harus berjalan kaki, naik kereta, dan menunggang kuda, seringkali dengan sedikit makanan, pakaian yang buruk, dan perawatan kesehatan yang tidak memadai.
Perjalanan itu dilanda penyakit, cuaca buruk, dan kelelahan. Pada akhir relokasi, diperkirakan 4.000 orang warga Cherokee meninggal karena sakit, kelaparan, dan kelelahan. Dan harus diingat, itu hanya pada suku Cherokee saja, belum lagi ribuan korban tewas mengenaskan suku lainnya dalam salah satu babak kelam di sejarah AS itu.
Meski terjadi pada awal abad ke-19, dampak dari pemindahan suku Indian itu masih ada dan kejadian traumatis ini telah merupakan bagian dari ingatan kolektif penduduk asli Amerika. Akibat banyak daerah tempat relokasi yang tidak sesubur tanah asal mereka, akibatnya kesulitan ekonomi masih terjadi di banyak komunitas penduduk asli AS hingga kini.
Hampir dua abad kemudian, gaung dari peristiwa gelap seperti yang terjadi pada kejadian "Trail of Tears" itu kembali terdengar ketika Trump pada 4 Februari 2025 menyebutkan bahwa AS akan mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza dan membangunnya kembali setelah rakyat Palestina direlokasi ke tempat lain. Relokasi itu disebutkan sebagai pemindahan permanen.
Dalam konferensi pers bersama ketua otoritas Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengatakan bahwa usai merelokasi warga Palestina ke luar Gaza, AS akan melakukan pembangunan ulang Gaza yang ia klaim dapat menjadikan wilayah kantong tersebut sebagai "Riviera di Timur Tengah".
Bagaimana dengan nasib warga Gaza, Trump di akun media sosial Truch Social pada Kamis (6/2) menyebutkan bahwa orang-orang Palestina akan dimukimkan kembali di "komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di wilayah tersebut.” Tentu saja, janji keamanan dan kondisi indah dari Trump bagi warga Gaza, mengingatkan pada pidato Jackson yang menyatakan akan meningkatkan "kesejahteraan dan kebahagiaan" suku asli Indian di AS.
Sontak saja, rencana Trump mendapat penolakan khususnya dari mereka yang masih menghargai penerapan konsep hak asasi manusia yang sesungguhnya. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk menyatakan bahwa sangat penting dalam membangun kembali Gaza menghormati sepenuhnya hukum humaniter dan HAM internasional.
Turk menegaskan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip dasar hukum internasional yang harus dilindungi oleh semua negara, serta setiap upaya pemindahan paksa atau deportasi orang dari wilayah pendudukan adalah tindakan yang dilarang keras berdasarkan aturan hukum tersebut.
Baca juga: Indonesia terus perjuangkan rakyat Palestina bertahan di Tanah Airnya
Baca juga: Liga Arab kembali menolak rencana pemindahan warga Palestina
Palestina berhak kembali
Kantor berita Turki, Anadolu mengutip ucapan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Negeri Ohio, AS, John Quigley, yang mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Gaza adalah keturunan warga Palestina yang diusir dari rumah mereka pada tahun 1948 dan mereka berhak untuk kembali.
Menurut Quigley, rencana Trump yang secara sepihak akan mengambil alih Gaza jelas melanggar hukum. Serta sangat aneh bila setelah terjadi genosida seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina, maka solusi yang ditawarkan adalah mengusir seluruh penduduknya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Boston, Susan M Akram, menegaskan bahwa rencana Trump melanggar berbagai ketentuan hukum internasional, karena tindakan pemindahan paksa itu sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Tidak lupa pula bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut rencana Trump sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia menegaskan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Palestina, serta menolak keputusan pihak asing atas masa depan rakyat Palestina. Namun, Trump seperti tetap bersikukuh dan meyakini bahwa pemerintahannya dapat membuat kesepakatan dengan sejumlah negara seperti Yordania dan Mesir antara lain karena AS telah "memberi mereka miliaran dolar setiap tahun".
Mesir sendiri dengan tegas menolak setiap usulan "yang bertujuan melenyapkan perjuangan Palestina dengan mencabut hak warga Palestina atau merelokasi mereka dari tanah historisnya, baik secara sementara maupun permanen". Sedangkan Raja Abdullah II dari Yordania kembali menegaskan dalam panggilan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa Yordania menolak segala upaya untuk mencaplok tanah Palestina atau merelokasi warga Gaza dan Tepi Barat.
Tidak hanya Mesir dan Yordania, negara-negara Arab lainnya seperti Kuwait menegaskan dukungannya terhadap hak Palestina untuk mendirikan negara merdeka, sekaligus mengutuk kebijakan permukiman Israel dan pemindahan paksa warga Palestina. Aljazair mengecam setiap rencana untuk mengusir warga Gaza, dengan memperingatkan bahwa skema semacam itu "mengancam inti perjuangan nasional Palestina."
Arab Saudi kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, sementara Uni Emirat Arab juga mengecam upaya pemindahan paksa, serta menyerukan solusi yang adil bagi konflik Israel-Palestina. Senada, baik Irak maupun Libya menyatakan penolakan keras terhadap setiap usulan atau upaya pemindahan paksa warga Palestina, serta menyerukan komunitas internasional mengambil sikap tegas.
Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa Indonesia senantiasa berjuang memastikan supaya rakyat Palestina tetap dapat bertahan di Tanah Airnya dalam rangka realisasi solusi dua negara.
Arrmanatha Nasir, usai menyampaikan laporan capaian pelayanan dan perlindungan WNI tahun 2024 di Kantor Kemenlu RI di Jakarta, Kamis (13/2), menegaskan bahwa "langkah-langkah yang tidak mendukung tercapainya solusi dua negara tentu tak akan kami dukung, dan mengeluarkan rakyat Palestina dari Gaza bukanlah langkah yang dapat mendukung realisasi solusi dua negara".
Reaksi tegas di dunia internasional sebenarnya sudah secara jelas menolak tindakan pemindahan atau relokasi permanen warga Palestina ke luar Gaza, tetapi kegetolan AS dalam membela apa pun bentuk kegadungan Israel sepertinya terus akan menjadi hambatan bagi terciptanya perdamaian yang stabil dan berkeadilan di Timur Tengah.
Padahal, Negeri Paman Sam itu sendiri dapat merenungi peristiwa "Trail of Tears" yang telah tertulis erat di lintasan sejarah mereka, di mana upaya pemindahan paksa hanyalah mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap para penduduk asli, berbagai suku Indian di AS, yang telah memiliki budayanya sendiri jauh sebelum pemukim dari Eropa datang ke daerah mereka.
Baca juga: Pakar: Arab Saudi dapat pengaruhi Trump soal Gaza
Baca juga: Mayoritas warga AS menentang rencana Trump kuasai Gaza
Baca juga: Legislator Jerman: Rencana Gaza Trump adalah kejahatan perang besar
Copyright © ANTARA 2025

 2 months ago
32
2 months ago
32