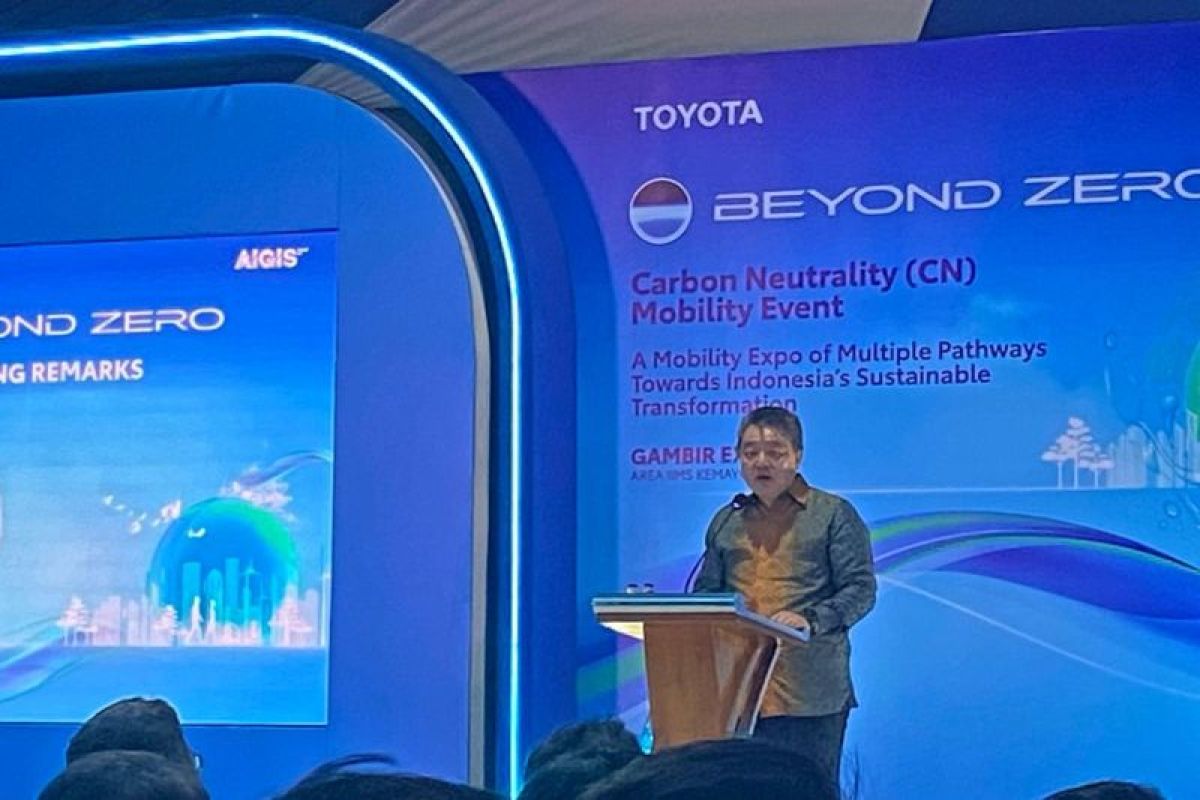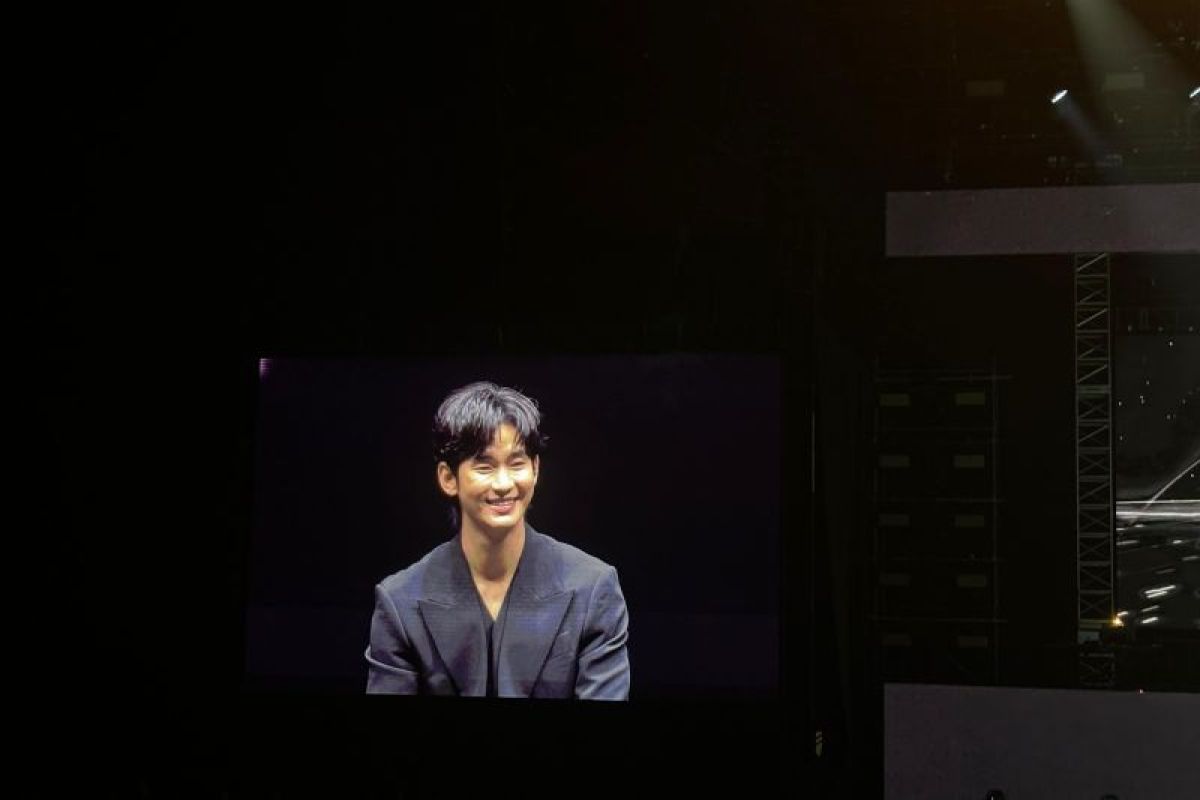TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Mouly Surya bercerita tentang proses panjang di balik pembuatan film Perang Kota (This City Is a Battlefield). Film ini diadaptasi dari novel klasik Jalan Tak Ada Ujung (1952) karya Mochtar Lubis yang berlatar Jakarta pada masa transisi pascakemerdekaan, pada 1946.
Pilihan Editor: Di Balik Layar Film Perang Kota Karya Mouly Surya
Kepada Tempo, Rabu 16 April 2025 di kawasan Palmerah Barat, Jakarta Barat, sutradara peraih Piala Citra itu mengungkapkan bahwa ketertarikan mengadaptasi novel tersebut muncul sejak 2018. Saat itu ia mulai membaca dan membayangkan potongan-potongan gambar dari cerita itu sebagai sebuah film.
Proses adaptasi ke layar lebar membutuhkan waktu hampir delapan tahun. Mouly menulis naskah dengan sembilan kali revisi untuk menterjemahkan kompleksitas batin tokoh-tokoh ke dalam bahasa visual. Ia juga harus menyesuaikan naskah agar film dapat dinikmati penonton internasional, termasuk melalui diskusi panjang dengan sejumlah produser luar negeri.
Perang Kota merupakan hasil produksi bersama tujuh negara yaitu Indonesia, Singapura, Belanda, Prancis, Norwegia, Filipina dan Kamboja. Untuk menciptakan suasana Jakarta pada 1946, tim produksi melakukan riset mendalam mengenai visual kota, busana, hingga kebiasaan masyarakat pada masa itu. Film ini pertama kali diputar di International Film Festival Rotterdam (IFFR) pada 9 Februari 2025, tayang di Belanda, Belgia, dan Luksemburg pada 17 April 2025, dan tayang di Indonesia pada 30 April 2025.
Apa alasan mengangkat Perang Kota dari karya Mochtar Lubis Jalan Tak Ada Ujung?
Waktu itu sudah lama sekali ya sebenarnya, menemukan bukunya. Sudah lama, ada di rak buku, tidak dibaca-baca. Tapi memang saya sangat menyenangi gaya penulisan Mochtar Lubis sebagai seorang sastrawan. Saya sebenarnya juga kuliah S1 jurusan Sastra Indonesia. Jadi memang selalu ingin mengikuti sastra-sastra Indonesia juga.
Kemudian ketika saya membaca buku Jalan Tak Ada Ujung itu, pertama kali pada 2018. Ketika membaca bukunya, kalau ingat bagian pembuka, dia (Mochtar Lubis) memainkan perjalanan waktu. Alurnya maju-mundur. Dari kerusuhan di Jalan Jaksa, ada Kamaruddin di rumahnya yang sedang memesan kopi, dan ada Guru Isa di sekolahnya.
Ketika saya membaca buku itu, ini mungkin terdengar cukup klise, entah kenapa saya seperti melihat semacam gambar di kepala saya. Padahal saat itu saya belum selesai membacanya. Saya kemudian langsung merekomendasikan kepada produser saya, sekaligus suami saya, Rama Adi untuk ikutan membaca juga dan untuk kemungkinan memfilmkan ini.
Dari Jalan Tak Ada Ujung menjadi Perang Kota. Mengapa judul film menggunakan Perang Kota?
Waktu itu saya bicara sama Pak Rushdy Hoesein, saya sedang melakukan riset. Dia merupakan salah seorang sejarawan yang cukup ekstensif. Saya ngobrol sama dia beberapa kali. Dia itu yang berkata, pada saat itu, sedang mengobrol perihal bukunya, ada cerita Gang Jaksa, dia bilang “Iya pada saat itu, Jakarta lagi perang kota.”
Mengapa Perang Kota baru dirilis pada 2025?
Ada alasan teknis. Alasan teknisnya adalah karena kami syuting pada tahun 2023. Film ini melibatkan koproduksi dari tujuh negara. Jadi prosesnya cukup kompleks. Waktu masuk ke tahap editing, ketika potongan gambar sudah mulai disusun, mencapai titik itu saja sudah cukup sulit. Karena harus banyak berdiskusi dengan para produser dari negara lainnya. Di tahap editing saja kami sudah harus mencantumkan teks terjemahan (subtitle) dari awal, karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia.
Filmnya itu baru selesai akhir tahun lalu, yang benar-benar sudah jadi, ya. Itu karena proses visual effect (VFX) yang cukup ekstensif. Pengerjaan VFX-nya sendiri tersebar di tiga negara: sebagian di Indonesia, cukup banyak di Amerika, dan juga ada yang dikerjakan di Belanda. Untuk bagian efek suara, kami bekerja sama dengan Prrancis.
Bagaimana pendekatan dengan keluarga mendiang Mochtar Lubis?
Beberapa dari mereka juga sudah menonton, dan pendekatannya kurang lebih sama. Kami menyampaikan, memang tertarik oleh bukunya dan ingin memfilmkan karya tersebut. Mereka sangat terbuka dan memberikan kebebasan yang luar biasa. Saya sangat bersyukur atas kebebasan yang mereka berikan dalam proses pembuatan film Perang Kota ini.
Apa tantangan terbesar dalam mengalihwahana karya novel ke film?
Tantangan terbesarnya adalah menemukan perspektif. Karena Mochtar Lubis sudah memiliki perspektifnya sendiri dalam buku itu. Interpretasi saya, mencoba memfilmkan versi dari apa yang saya rasakan. Saya merasakan kemarahan yang ia tuangkan, saya merasakan kesehariannya. Dan kemarahannya itu bukan kemarahan yang besar dan hadir dalam keseharian. Saya berusaha memfilmkan nuansa itu.
Selain menjadi sutradara, Anda menulis naskah Perang Kota. Bagaimana prosesnya?
Proses penulisannya sangat panjang. Saya bekerja dengan beberapa produser dari luar negeri, salah satunya Isabelle Glachant dari Prancis. Saya sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan dia di Marlina, Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017). Dia adalah salah satu koproduser di film tersebut, dan kami kembali bekerja bersama di proyek ini.
Proses penulisannya, jujur saja, mungkin ini adalah skenario paling kompleks yang pernah saya buat. Dan sejauh ini, juga yang paling sulit untuk saya capai. Tapi saya juga merasa skenario ini bisa dibilang sebagai yang terbaik yang pernah saya tulis sejauh ini.
Saya merasakan betul kompleksitasnya, tantangan-tantangannya, dan semua prosesnya. Dari bukunya sendiri saya mendapat banyak inspirasi. Terutama dari cara penyampaiannya—karena membaca dan berbicara itu kan dua hal yang sangat berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan buku-buku pop zaman sekarang. Cara mengonstruksi kalimatnya sangat berbeda, dan itu yang saya coba tiru, atau istilahnya saya coba tiru.
Berapa lama Anda menulis naskah untuk Perang Kota?
Prosesnya dimulai sejak 2018, dan itu berjalan on and off. Jumlah draf ada 9. Dan perubahan-perubahannya bukan yang kecil-kecil. Perubahannya tuh besar. Banyak yang berubah secara signifikan. Jadi, ya, drafnya memang banyak dan memakan waktu yang cukup panjang. Proses revisi dan pengembangan selama hampir 8 tahun dari 2018.
Banyak detail klasik dan nuansa era 1946 Indonesia saat itu, bagaimana proses riset meghadirkan nuansa tersebut?
Kami ke perpustakaan, mencari gambar, mencari video, kami berbincang dengan sejarawan. Dunia Jakarta yang ingin saya tampilkan waktu itu penuh dengan memori. Saya ingat, salah satunya adalah tentang keluarga saya. Mendiang paman saya lahir pada 1921, mendiang ayah kandung saya lahir pada 1931. Mereka berdua, kalau datang ke acara-acara, suka pakai tuksedo, pakai topi. Ayah saya bahkan suka pakai gesper seperti Hazil. Potongan celananya pun khas.
Kalau paman saya, karena dia profesor saat bicara suka mencampur bahasa. Misalnya sekarang kita bicara pakai bahasa Inggris, dulu mereka pakainya bahasa Belanda. Dan itu yang saya ingin hadirkan dalam film ini. Karena kita sedang membicarakan Jakarta, kota besar. Jakarta sebagai kota besar saat itu tentu memiliki masyarakat berpendidikan dan berwawasan luas. Maka dari itu, tokoh seperti Guru Isa, yang di buku digambarkan sebagai guru dan pemain biola, dia bermain (karya-karya) Frederic Chopin dalam permainannya.
Ada tantangan menghadirkan bangunan-bangunan lama pada masa itu?
Tadinya melihat Jakarta seperti ini—ini kali-kali buat apa sih, kanal-kanal ini? Tapi ketika saya ke Amsterdam untuk pertama kalinya, tiba-tiba semuanya jadi jelas: “Oh, ini yang mereka coba lakukan.” Sebenarnya kota seperti inilah yang mereka bangun.
Kalau melihat foto-foto zaman dulu, terasa sekali bahwa memang ada niat untuk menjadikan Jakarta seperti itu. Maka dari itu, kami juga memilih kota Semarang sebagai salah satu lokasi. Karena menurut saya, kita sedang bicara tentang kali—yang nama kerennya sebenarnya kanal. Karena memang itu benar-benar jadi kanal, dan kanal-kanal itu masih punya fungsi yang serupa.
Tokoh Fatimah (Ariel Tatum) mengenakan dress klasik dalam film, apa ada pertimbangan khusus?
Ketika kita dijajah, seperti apa sih rupa orang-orang kita yang dijajah, khususnya di Jakarta pada saat itu? Orang-orang yang paling dekat dengan penjajah, mereka seperti apa? Itu juga saya coba aplikasikan ke dalam aspek kostum.
Soal pakaian, saya pernah berdiskusi dengan seorang sejarawan. Menurut dia, bayangan Fatimah itu pakai kebaya. Tapi saya lama-lama berpikir, dengan Fatimah versi saya—mungkin ya, Fatimah memang bisa saja pakai kebaya. Tapi Fatimah saya akan memakai vintage dress.
Karena saat itu, dress memberikan kebebasan bergerak. Dia adalah seorang perempuan dengan semangat yang bebas (free spirit). Dan mungkin pada masa itu, cara pandangnya terhadap hal yang keren ya mirip dengan kita sekarang: yang keren itu seperti orang Belanda, seperti orang Barat pada zaman itu.
Latar cerita berada Jakarta, tapi mengapa lokasi syuting tidak ada di Jakarta (Surabaya, Yogyakarta, Klaten, dan Ambarawa)?
Banyak sekali elemen teknis dan logistik, itu jadi pertimbangan utama. Di balik itu, tentu saja ada inspirasi dari kota-kota yang ada di Jakarta. Awalnya, ketika saya menulis, yang ada di bayangan saya adalah Toko Merah yang ada di Jakarta. Tapi seiring waktu, itu berkembang dan menyesuaikan dengan lokasi yang tersedia. Secara logistik dan kemungkinan syuting di keramaian, letak geografis—itu agak sulit dilakukan di Jakarta.
Biodata Mouly Surya
Nama: Nursita Mouly Surya atau Mouly Surya
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 10 September 1980
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suami: Rama Adi
Penghargaan: Sutradara Terbaik Festival Film Indonesia 2008 dan 2018 (fiksi. dan Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak)